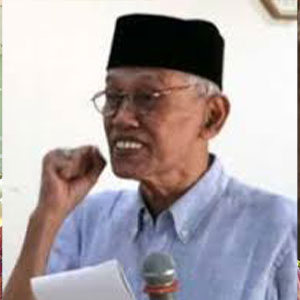 Helmi Ali atau di kalangan aktivis lebih dikenal dengan panggilan Bang Helmi lahir di Pinrang, Sulawesi Selatan pada tanggal 10 April 1954. Ia adalah aktivis dan penggerak gerakan kultural.
Helmi Ali atau di kalangan aktivis lebih dikenal dengan panggilan Bang Helmi lahir di Pinrang, Sulawesi Selatan pada tanggal 10 April 1954. Ia adalah aktivis dan penggerak gerakan kultural.
Ayahanda Helmi adalah seorang tokoh kesohor di tubuh organisasi sosial kemasyarakatan, Nahdlatul Ulama. Di organisasi tersebut, sang ayah pernah menjabat sebagai PJS Rais Aam PBNU. Ayahnya bernama K.H. Ali Yafie sementara ibundanya bernama Aisyah Umar. Saudara sekandung Helmi bernama Saiful Ali Yafie, Badru Ali Yafie, dan Azmi Ali Yafie.
Helmi menempuh pendidikan di Sekolah Arab DDI (Darud Da’wah wa al-Irsyad) di Jampue, Pindang, kemudian melanjutkan pendidikan menengah dan tingkat atas di Makkasar. Pada tahun 1970-an ia mengikuti ayahandanya ke Jakarta dan menetap di ibukota itu. Pendidikan sarjananya ia tempuh di jurusan Perbandingan Agama & Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan selesai pada tahun 1980-an. Sementara pendidikan masternya ia tempuh di Universitas Indonesia.
Nur Khalik Ridlwan menyebut Helmi sebagai orang yang aktif di sayap kultural. Ia juga banyak terlibat dalam gerakan-gerakan untuk menjaga dan mengembangkan Khittah 1926 Nahdlatul Ulama. Di samping itu, ia juga aktif dalam dalam pengorganisasian di berbagai komunitas di Indonesia. Mulai dari kelompok pengusaha kecil, mengenah, aktivis NGO hingga kelompok basis jaringan beberapa pondok pesantren di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Madura.
Helmi juga tercatat pernah aktif dalam berbagai organisasi, misalnya LP3ES, P3M, Lakpesdam PBNU, dan Badan Pengawas Perhimpunan Rahima. Di LP3ES ia pernah menjabat sebagai tenaga motivator lapangan program KIP (Kampung Improvement Progress), kerja sama LP3ES dengan UNICEF pada tahun 1980-an. Sementara di P3M ia pernah aktif sebagai Kepada Bidang untuk Penelitian dan Pengembangan terhitung sejak tahun 1987 hingga 1990. Karier Helmi di Lakpesdam PBNU sudah dimulai sejak masa pertama, bahkan bisa disebut ia termasuk bagian tim pendiri. Ketika menceritakan kariernya di Lakpesdam PBNU ia menyebut bahwa pada tahun 1984 ia oleh sahabatnya, Manshour Fakih diajak untuk mengikuti pertemuan di Kantor PBNU dalam rangka pembentukan Lakpesdam.
Periode awal Lakpesdam, Helmi hanya ikut merumuskan program kerja. Namun setelah berjalan setahun, Lakpesdam mandeg. Akhirnya ia kembali diajak untuk membantu LAKPESDAM. Ia menuturkan, “Kali ini yang ajak saya adalah Pak Umar Basalim (sekarang Guru Besar di UNAS Jakarta) dan Mas Fahmi Saifudin Zuhri. Saya diminta membuat program-program kerja LAKPESDAM. Pada Periode kedua ini, saya sempat aktif sebagai sekretaris LAKPESDAM. Sementara ketuanya adalah MM Billah.”
Direktur Lakpesdam pada waktu itu adalah Said Budairi, hanya saja menjelang Muktamar NU di Krapyak Yogyakarta, Helmi bersama MM Billah mengundurkan diri. Walau demikian ia masih aktif dan terlibat dalam tim yang menyusun draf program NU. Beberapa tahun berikutnya ia kembali masuk Lakpesdam dan menjabat sebagai wakil ketua bersama dengan MM Billah.
Karier Helmi tidak hanya di Lakpesdam PBNU. Ia juga aktif dan bahkan mendirikan organisasi CPSM (Circle of Participatory Social Management). Tercatat Helmi pernah bekerja di beberapa organisasi dan projek antara lain sebagai Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemili untuk Rakyat (JPPR) pada tahun 1993-2003; Konsultan Program Pengendalian Hama Terpada Indonesia dan Inter Country Program, FAO pada tahun 1996-2001; Pengurus FIELD (Farmes Initatives For Ecologival Livelihoods and Democray), Jakarta sejak 2001-Sekarang; Konsultan Direktorat Perguruan Tinggi, Departemen Agama Republik Indonesia untuk pengembangan Metodologi Penelitian dengan Pendekatan Partisipatory Research Actian (PAR); Tenaga pengajar tamu PAR di berbagai perguruan tinggi yang berada di bawah Direktorat Perguruan Tinggi, Departemen Agama Republik Indonesia pada tahun 2004-2009, Anggota Dewan Ethich Komnas Perempuan sejak tahun 2016-Sekarang; Konsultan Direktorat Jenderal BIMAS, Kementrian Agama Republik Indonesia dari tahun 2017-Sekarang.
Tokoh dan Keulamaan Perempuan
Perjumpaan Helmi Ali dalam kaitannya dengan isu dan perjuangan untuk perempuan pertama kali justru ia alami di dalam keluarganya. Helmi berasal dari kelurga kiai di kampung yang pastinya memiliki keistimewaan. Ketika pindah ke kota yang secara budaya berbeda, maka semua pekerjaan, termasuk pekerjaan domestik pasti ditangani oleh keluarga, terutama ibunda tercintanya.
Di lingkungan keluarga Helmi, sang ayah, Kiai Alie Yafie, sejak awal begitu menghormati istrinya. Sikap itu kemudian yang ditiru oleh anak-anaknya yang semuanya adalah laki-laki. Dalam pengambilan keputusan, ibundanya mendapatkan posisi yang setara. Ketika misalnya terjadi perselisihan terkait benda yang hendak dibeli lalu tak menemukan kata sepakat, maka keputusan akhir diambil oleh sang ibu. Ketika libur sekolah, maka tugas-tugas domestik seperti menyapu dan mencuci baju diambil alih oleh Helmi dan saudara-saudaranya. Pengalaman-pengalaman itu kemudian mengilhami Helmi untuk menekuni isu-isu perempuan.
Setelah itu, jalan perjuangan Helmi terhadap isu perempuan berlanjut di P3M sejak awal tahun 1990-an. Di organisasi yang dipimpin oleh Kiai Masdar Farid Mas’udi itu ada program bernama Fiqh al-Nisa’ yang secara khusus membedah isu-isu perempuan. Melalui organisasi ini, Helmi terus mematangkan dan memperjuangkan isu-isu perempuan yang digelutinya. Kajian Fiqh al-Nisa itu kemudian mengilhami berdirinya Rahima. Helmi Ali tercatat sebagai salah satu tim pendiri, tepatnya pada tahun 2000.
Rahima dalam pandangan Helmi Ali adalah lembaga yang concern pada pendidikan kader ulama perempuan. Selama di Rahima ia beberapa kali membantu mengembangkan berbagai program utamanya dalam bidang pendidikan. Pada tahun 2004-2010, ia ikut merancang program dan menjadi fasilitator PUP dan program pendidikan untuk tokoh agama yang melibatkan aktivis pesantren, ormas, dan perguruan tinggi yang menjadi jaringan kerja Rahima. Pada tahun-tahun itu, ia juga aktif dalam program Madrasah Rahima untuk guru-guru agama menengah di daerah Tapal Kuda (Banyuwangi, Situbondo, Jember dan Bondowoso). Pada tahun-tahun berikutnya, program yang sama juga dikembangkan di Jakarta.
Pada tahun 2003 hingga 2006 ia ikut serta membantu PUAN AMAL HAYATI mengembangkan program (Merespons kekerasan terhadap perempuan) untuk pesantren jaringan kerja PUAN AMAL HAYATI. Selain itu, ia juga banyak terlibat dalam merancang program Fahmina, sebuah organisasi yang concern terhadap isu gender di Cirebon. Hal yang sama juga terjadi pada organisasi Alimat, Helmi juga terlibat merancang program.
Ulama perempuan menurut Helmi sebagaimana ia sandarkan pada hasil kongres KUPI adalah bukan terkait jenis kelamin melainkan lebih pada ideologi. Jadi ulama perempuan adalah ulama yang melihat persoalan menggunakan kacamata atau perspektif perempuan. Oleh karena itu, mereka harus memiliki kepekaan terhadap persoalan-persoalan perempuan, dan mereka bisa laki-laki atau perempuan. Dari definisi ini, jika ada perempuan yang memenuhi syarat disebut ulama hanya saja ia tak memiliki perspektif perempuan maka ia tak bisa disebut ulama perempuan.
Terkait keulamaan perempuan, Helmi menyebut bahwa sebenarnya ulama perempuan di Indonesia sangat banyak, baik zaman dulu atau sekarang, di antaranya seperti Rahma el-Yunusiah dan Nyai Khairiyah Hasyim. “Akan tetapi, problemnya memang mereka tidak menonjol, tidak tampil di permukaan. Kenapa demikian? Sebab panggungnya dikuasai ulama laki-laki,” tutunya.
Selain itu, jarang ada ulama perempuan yang memiliki karya atau mempunyai karya akan tetapi tidak banyak diketahui orang. Kecuali ulama perempuan yang memiliki kiprah luar biasa. Hal ini sebenarnya bisa disebut meminggirkan atau pengabaian terhadap mereka. Padahal secara kualifikasi, mereka sangat memenuhi syarat. Peminggiran dan pengabaian terhadap peran dan kiprah ulama perempuan ini, dalam pandangan Helmi, memiliki unsur kesengajaan. Dari sejak awal Islam, posisi perempuan sangat kuat. Misalnya, Aisyah bahkan pernah menjadi guru dan tempat bertanya para sahabat. Dalam waktu yang lain, Aisyah sering dimintai klarifikasi terkait beberapa masalah. Hingga ada kitab yang berjudul al-Ijabah fima Istadrakathu al-Aisyah. Contoh lainnya adalah Siti Nafisah, yakni perempuan yang menjadi guru dan rujukan banyak orang di era cucu nabi
Namun beberapa tahun berikutnya, dengan alasan khawatir terjadi fitnah, peran perempuan di ruang-ruang publik mulai dipinggirkan kembali. Melihat perubahan ini, Helmi berpandangan bahwa sebenarnya, yang paling memengaruhi marginalisasi kaum perempuan adalah faktor politik. Pihak yang paling diuntungkan dalam keadaan yang demikian adalah laki-laki. Sebab laki-laki secara naluriah memiliki keinginan untuk lebih dominan dalam kehidupan. Sementara perempuan secara karakter adalah mengalah.
Fenomena politik yang mengakibatkan peminggiran perempuan kemudian makin diperkuat dengan budaya yang pada waktu itu tidak berpihak kepada kaum perempuan (baca: patriakhi). Dan puncaknya, tafsir keagamaan yang bias semakin mengukuhkan peminggiran tersebut. “Jadi penyebab secara lengkap kenapa peran perempuan dalam ruang publik makin tidak tampak adalah politik, kemudian dikuatkan oleh budaya dan puncaknya adalah penafsiran keagamaan yang tidak proporsional,” simpulnya.
KUPI menjadi tonggak sejarah bagi keulamaan perempuan. Secara tidak langsung acara ini juga memproklamirkan bahwa ulama perempuan itu eksis dan ada. Proklamasi posisi ini makin menemukan momentumnya karena dalam acara ini ada fatwa dan rekomendasi untuk merespon beberapa masalah krusial yang berkaitan dengan isu perempuan dan anak. Helmi Ali menambahkan bahwa KUPI bukanlah satu organisasi, melaikan semacam forum yang didukung oleh beberapa organisasi. Dalam KUPI ada yang disebut dengan Majelis Musyawarah KUPI yang diisi oleh para penggagas awal. Tujuan Majelis ini untuk mengawal rekomendasi yang telah dirumuskan dalam KUPI.
Tantangan utama gerakan perjuangan kesetaraan untuk perempuan, menurut Helmi, adalah isu politik yang ingin meminggirkan perempuan. Persoalan ini didukung oleh budaya dan tafsir keagamaan yang bias. Oleh karena itu, gerakan ulama perempuan ini harus masuk dalam dunia politik. Meskipun maknanya tidak harus menjadi anggota parpol. Poinnya adalah bagaimana menyuarakan kepentingan-kepentingan perempuan kepada pengambil kebijakan agar kebijakan yang dilahirkan berpihak kepada kaum perempuan.
Secara keseluruhan, Helmi menuturkan, progres perjuangan untuk perempuan makin bagus. Kehadiran ulama perempuan sekarang sangat diperhitungkan. Misalnya, Majelis Ulama Indonesia merekrut beberapa pengurus yang merupakan tokoh yang bisa disebut memiliki perspektif perempuan, seperti Nyai. Hj. Badriyah Fayumi dan Dr. K. H. Abdul Moqsith Ghazali.
Karya-karya
Helmi Ali akitif menulis dan melahirkan banyak karya, baik berupa buku, artikel jurnal, maupun artikel popular. Karya-karyanya yang berupa buku di antaranya adalah:
- Politik Islam dalam Lintasan Sejarah, terjemah dari Buku, W. Montgomery Watt, Islamic Political Tought, (Edinburgh University Press, 1980; P3M Jakarta, 1988).
- Madrasah Rahima (Penerbit Rahima, Jakarta 2009).
- Modul Pendidikan Ulama Rahima (Jakarta: Penerbit Rahima, 2009).
- The Rahima Story. (Jakarta: Penerbit Rahima, 2010).
- “Jalan Tasawuf Moderat”, Pengantar dalam B. Wibowo, Bertasawuf di Zaman Edan. (Republika 2016).
- “Nasib Ulama Perempuan”, prolog dalam Helmi Ali Yafie (Ed.), Jejak Perjuangan Ulama Perempuan di Indonesia, 2017).
- “Walisanga, dan Penyebaran Islam di Jawa”, Pengantar dalam B. Wiwoho, Islam Nusantara dan Jalan Dakwah Sunan Kalijaga (Jakarta: Penerbit Iman, 2017).
